Menata Setangkup Rasa
“Ini!” Yogi menyodorkan sebuah bingkisan tepat ke depan hidungku.
“Apa ini?” Mataku spontan berkedip tiga kali karena kaget, namun bingkisan itu kusambut juga ragu-ragu.
“Kamu ulang tahun, kan? Makanya, ini…”
“Haaa?” aku bingung seketika dan reaksi selanjutnya yang juga diluar kendaliku adalah… tertawa terbahak-bahak!
“Apaan, sih! Kalau nggak mau, ke sinikan! Kuambil lagi!” sungut Yogi sambil buru-buru merampas bingkisan bersampul cokelat itu. Tanpa dibuka pun sepertinya aku bisa menebak apa isi di dalamnya. Buku yang tebal dan ukurannya menyerupai buku tulis yang digulung, lalu dibalut dengan kertas kado bermotif batik coklat. Yang membuatnya pasti sudah berusaha keras membungkusnya serapi mungkin. Ya, ampun! Mimpi apa aku semalam, Yogi mendadak jadi romantis!
Jangan menyangka kami adalah sepasang kekasih, apalagi menuduh kami sedang pacaran, pun pedekate. Tidak! Itu tak akan pernah terjadi. Yang kuingin sekarang adalah menjadi istrinya!
“Yogi… Yogi… Ultah-ku, kan kemarin. Sini!” Aku masih tak bisa menghentikan tawaku. Kurebut bingkisan itu kembali.
“Ya, ya, kemarin aku sibuk, nggak sempat beli hadiah. Apalagi ngebungkusin sampai serapi ini. Ntar, kalau nggak dibungkus… situ ngambek lagi deh, kayak tahun lalu…” jawabnya dengan cengiran khas Yogi.
Aku tak menjawab lagi, tahun lalu ia memberi sebatang cokelat untuk ulang tahunku. Cokelat yang dibelinya di tengah jalan ketika akhirnya ia ingat hari itu adalah ulang tahunku. Sontak saja aku menolak, masa setelah disindir habis-habisan, baru dia ingat itu hari ulang tahunku. Waktu itu aku di boncengannya, kami ada perlu ke rumah Bibi An mengantar dagangan Mami.
“Hayah, aku baru ingat! Sebentar ya!” Yogi mendadak mengerem motor tepat di sebuah kedai kecil yang berjualan soft drink dan snack. Berat dugaanku ia sebenarnya haus dan ingin minum saat itu juga.
Ia berhenti setelah aku bilang, ia bukan teman yang baik karena tak pernah sekali pun memberi hadiah di hari ulang tahunku. Ia serta merta membelikan sebatang coklat dan menyodorkannya padaku, “Selamat ulang tahun, Non!” katanya sambil membungkuk memberikan cokelat murahan itu.
Aku tak sudi dikatakan matre kalau kutolak karena itu cokelat murahan, makanya kutolak dengan kaliamat, “Ogah, ah! Hadiah apaan itu, dibungkus pun tidak!”
Yup! Itu setahun yang lalu di 29 Februari. Hari ini sudah ada kemajuan sepertinya. Aku tak lagi ‘berbalas pantun’ dengan Yogi. Dengan khusyuk kubuka bingkisan itu.
“Ya, Ampun, buku TTS! hahahaha….” Tawaku pecah lagi. Kali ini Yogi ikut ber-koor denganku menghasilkan duet yang sungguh mengharukan. Air mataku sampai ikutan keluar karena tak sanggup menahan lucu. Dasar Yogi gila! Kenapa Mami bisa mengambil dia menjadi anak, dan sampai hari ini, sudah lebih sepuluh tahun, aku tinggal seatap dengannya.
Seiring pengetahuanku tentang pergaulan, saat kelas satu SMA, aku mulai mengenakan hijab. Tapi interaksi kami berdua masih seperti biasa. Reaksi Yogi sendiri biasa saja ketika aku memutuskan berjilbab setiap kali aku keluar dari kamarku.
“Mau kemana, Ran?” Itu saja pertanyaannya ketika dilihatnya aku makan, kemudian duduk di ruang tamu dengan jilbab yang masih rapi.
“Nggak kemana-mana, eh.” Jawabku sambil terus mengganti channel siaran teve.
Ah, Yogi! Tak ada yang mengatakan ia sangat tampan. Tapi bagiku, Yogi nyaris mengisi seluruh rongga-rongga hatiku. Di sekolah ia tak begitu populer, biasa saja. Aku adik kelasnya sejak SD sampai SMA. Sekarang kami sudah kuliah. Satu universitas, beda jurusan.
Semuanya tak ada yang aneh. Dengan kedua kakak lelaki kembarku, ia tak pernah diperlakukan berbeda oleh Mami dan Papi. Umurku bertaut enam tahun dengan Kak Fadhil dan Kak Farhan. Jadi bisa dibilang aku lebih sering bermain dengan Yogi ketimbang dengan dua kakakku yang sekarang sudah menikah dan bekerja di salah satu BUMN itu.
Yogi yang kuliah di teknik sipil hampir terkejar olehku yang saat ini sedang skripsi di jurusan teknik kimia. Terkadang aku merasa bersalah, sebab ia sudah banyak sekali membantuku menyelesaikan tugas kuliah ataupun sekadar mengantar jemputku saat menginap di rumah teman untuk meyelesaikan tugas. Ah, tapi biar saja, itu kan karena dia juga nggak giat-giat amat kuliahnya.
Hm, tapi ia juga tahu diri. Dengan kesadaran penuh, ia jadi kaki tangan Mami dalam bisnis sampingan Mami. Terkadang ia juga ikut teman-temannya mengerjakan side job supaya tak terlalu membebani Mami dan Papi. Apalagi untuk ongkosnya pulang ke kampung Kakeknya minimal setahun sekali, Yogi biasanya memakai uang tabungannya sendiri.
Itu menambah deretan kekagumanku padanya. Walau Mami dan Papi tak pernah menagih pamrih padanya, ia tak pernah memanfaatkan begitu saja. Aku juga merasa, Yogi sayang sekali padaku. Tentu saja, aku yakin itu. Sampai hari itu…
“Ran, lagi sibuk, nggak?” Yogi tiba-tiba menyapaku pagi itu.
Tanggal yang tertera di kalender memang merah. Jumat April tanggal 6, hari wafatnya Yesus Kristus. Aku sendirian di teras dan harus mengejar revisi skripsi, jadi tak terlalu peduli dengan tanggal merah. Tak ada bedanya dari hari ke hari, asalkan tetap bisa bersama Yogi, setiap tanggal terasa istimewa.
“Nggak lihat, nih, aku lagi ngapain? Hm, tumben pagi-pagi nggak bau iler lagi. Mau berangkat kerja?” jawabku dengan pertanyaan juga. Aku hanya meliriknya sekilas sambil terus berkonsentrasi dengan lembaran word 2010 di notebook-ku
“Hm, nggak, sih. cuma perlu ketemu teman sebentar… ngg… ” jawabannya menggantung. Kuoper sekilas biji mataku ke arahnya tiba-tiba saja wajahnya rada serius dan agak tegang, menurutku. Aku jadi bingung dengan sikap ganjilnya. Tapi aku menunggu ia menyelesaikan jawabannya sampai tuntas.
Satu, dua, tiga… hingga detik kesepuluh Yogi hanya mengedarkan pandangannya tak tentu arah dan menyisir helaian rambutnya dengan jemari. Aku masih menunggu sambil terus menelusuri huruf-huruf dan re-type beberapa referensi yang sudah dicoret-coret dosen pembimbingku saat assistensi siang kemarin.
“Iiih, apaan, sih?” tanyaku turut frustasi.
Mami muncul tiba-tiba, “Eh, belum berangkat, Gi? Kebetulan, nih. Tolong angkat kardus yang di sudut sana.”
“Oh, barang baru, Mi?” Tanya Yogi sambil beralih ke pintu masuk.
“Iya, baru sampai semalam. Harusnya kemarin siang, sepertinya ada ganguan sampai harus tertunda gini. Jadi ketemu anak itu hari ini?”
Aku masih bisa mendengar obrolan Yogi dan Mami. Yogi mengiyakan dengan jawaban yang sedikit canggung, “I.. iya, Mi. Ke rumah Ihsan dulu, sih. Ketemuannya berempat di pustaka kampus. Dia bareng temennya. Ya, udah, Mi. Yogi langsung cabut aja, ya? Itu si Rani lagi serius amat, Mami aja yang ngabarin. Doakan Yogi, ya, Mi.”
Kepalaku spontan beralih dan berputar sekian derajat demi mendengar kalimat “Mami aja yang ngabarin”, memangnnya ada peristiwa penting apaan, sih? Batinku. Yogi sudah berlalu dengan sepeda motor yang sudah sejak tadi di-starter-nya.
“Ada apa, sih, Mi?” tanyaku spontan sambil mendongak mencari wajah Mami yang mulai berjalan ke arahku kemudian mengambil posisi tepat di sebelahku. Kursi kayu panjang tua kami berdecit menahan tubuh gempal Mami yang wajahnya tetap cantik di usia peraknya.
“Mungkin ini masanya bagi Yogi untuk menyusul Kak Fadhil dan Kak Farhan,” jawab Mami sambil tersenyum tipis penuh misteri, itu menurutku. Karena kalimat jawaban Mami semakin membuatku penasaran.
“Aku nggak ngerti. Yogi udah dapet kerjaan di bank juga? Tapi, kan, dia belum lulus…” kejarku.
“Bukan itu…”
“Terus?”
“Dia mau… aduh! Mami lupa, apa tuh, namanya? Taruf gitu…”
“Taruk? Apaan?” Aku makin penasaran saja sebab tak ada bayangan, tak bisa kuterka sedikit pun. Tepatnya aku tak bisa menduga ke arah mana pembicaraan ini dituju.
“Yogi bilang, ada kakak tingkatnya yang mau ngenalin dia sama calon istri.”
“Ih, Mami berbelit amat, sih. Maksudnya kakak tingkatnya nyari istri gitu? Terus apa hubungannya sama Yogi, lagi? Sejak kapan dia jadi mak comblang, Hihi…” aku geli sendiri jadinya membayangkan Yogi nyomblangin kakak tingkatnya. Kok bisaaa?
“Kamu kok jaka sembung gitu, sih, Ran. Yoginya yang mau cari istri! Dia bakal married dalam waktu dekat ini.”
CTAR! Seperti mendengar gelegar petir. Aku hanya melongo.Kukedipkan mataku sekejap untuk kembali hadir di samping Mami.
“Hm, memang baru rencana, sih. Mami dan Papi udah bicara. Rasanya nggak ada masalah, yang penting dia punya komitmen untuk menyelesaikan kuliahnya yang tinggal skripsi itu.” Sambung Mami lagi sambil berlalu.
Mami sama sekali tak memerhatikan wajahku yang mirip bulan kesiangan.
“Mami dan Papi pengennya Yogi lebih giat kayak kamu, Ran. Tapi setiap orang kan berbeda, ada yang lancar, ada yang mandeg juga.” Mami terus bicara sambil membuka paviliun yang sudah disulap menjadi toko kain dan pakaian.
“Idih, serius amat, Ran. Seperti yang kami duga, kamu pasti nggak terlalu tertarik dengan obrolan ini. Tapi Yogi kan udah seperti kakak kamu juga. Makanya kabar bahagia gini, kamu kudu dikasih tahu…” Mami terus bicara sambil memajang baju gamis ke sebuah menequin. Sementara jantungku pacunya tak lagi normal. Mataku memandang ke arah LCD notebook tapi pikiranku tak lagi di sana.
Mataku mengerjap sekali lagi. Satu rasa yang bercokol di hatiku. Nelangsa. Aku sama sekali tak bingung dengan perasaan ini, sebab aku sudah hafal sekali, apa sebenarnya nama perasaan yang aku simpan untuk sebuah nama selama ini. Aku menyukainya sejak SMP! Ah!
“Ta.. tapi, Mi… bukankah ini seperti tergesa sekali?” Aku semester akhir sekarang, usiaku 21 tahun. Yogi 23 tahun. Pertanyaan yang aku lontarkan barusan, bukankah itu pertanyaan yang tepat? Aku orang yang paling bisa mengendalikan diri. Walau wanita, aku termasuk ke dalam tipikal yang mampu menyeimbangkan kedua belah otakku. Itu menurutku.
“Ya, kami juga awalnya berpikir begitu. Tapi Yogi bilang ini bukan tergesa tapi disegerakan. Katanya, insyaallah dengan adanya pendamping hidup, dia menjadi lebih giat menyelesaikan kuliah. Banyak alasan lainnya yang memang bisa diterima Mami dan Papi, Ran. Ya, kamu tahu sendirilah, Yogi itu bagaimana. Walau usianya masih 23 tahun, tapi dia udah lebih matang dibanding anak-anak muda lainnya. Didikan Kakeknya kali, ya. Seingat Mami, orang tuanya Yogi dulu memang orang alim, Ran. Mereka banyak ngerti agama. Waktu kecelakaan itu usia Yogi masih 12 tahun, tapi kayak anak udah ngerti banget tentang takdir.” Tiba-tiba Mami seperti menerawang ke 11 tahun silam.
Mami memanggil kami bertiga. Kak Fadhil, Kak Farhan dan aku. Kami didudukkan bersama di sekeliling meja makan. Hari itu masih sore, belum saatnya makan malam, tapi Mami menyuruh kami duduk di sana. Sudah menunggu seorang anak lelaki dengan penampilannya yang terkesan lelah. Kaos oblong dongker yang dikenakannya sudah usang. Posturnya sedang, tidak terlalu pendek ataupun tinggi. Tulangnya yang sedikit menonjol menandakan berat badannya tak ideal dengan tinggi badannya. Ia mencoba memandang ke arah kami bertiga dan melarik senyum.
“Fadhil, Farhan, Rani, kenalin… ini Yogi. Hm, Yogi apa nama lengkapnya?” Papi memulai percakapan dan mencoba membuat anak di depan kami itu terbiasa.
“Ahmad Yogi Al-karim, Paman.” Jawabnya dengan mata yang mulai berbinar.
Padanan nama yang ganjil, pikirku. Tapi sepertinya dia cukup bangga memiliki nama aneh seperti itu. Belakangan baru kutahu, kalau Yogi itu singkatan nama ayah dan ibunya.
Sejak hari itu kami memiliki saudara baru. Adik untuk kak Fadhil dan Kak Farhan, kakak lelaki baru untukku. Pupus sudah mimpiku punya saudara perempuan. Akulah anak tercantik yang Mami Papi miliki hingga hari ini.
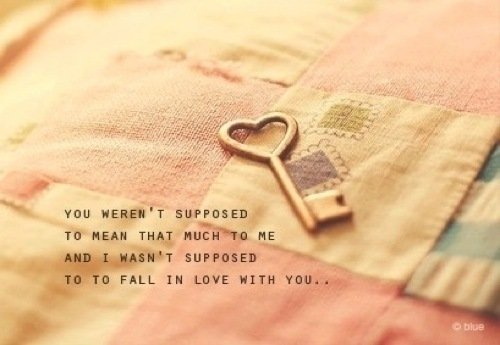
Sekali lagi, tak ada yang mengatakan Yogi itu tampan. Matanya saja yang mungkin semenarik Song Seung Heun. Lainnya tak ada yang unik. Tapi bagi yang benar-benar mengenalnya seperti aku, sosok Yogi bukan sekadar mahasiswa biasa yang sering mengulang mata kuliah dengan adik tingkat, pendiam, tak aktif di organisasi kampus, dan tidak populer di kalangan gadis-gadis.
Dia baik. Bukan! Bukan itu saja. Lebih dari itu! Walaupun jauh dari kesan romantis seperti yang diimpikan banyak gadis, aku belum pernah menemukan anak sepenurut dan sesantun dia. Untuk Papi, Mami, Kakeknya, untuk orang tua teman-teman lelakinya yang bejibun. Dia populer di kalangan orang tua. Imam di masjid kampung kami juga mengenalnya. Dia selalu menunjukkan keberadaanya dalam diamnya. Itulah Yogi di mataku.
Bagiku ia tak ada tandingannya. Gentle man yang dikatakan orang-orang, itulah Yogi-ku. Ya, Yogi-ku. Aku selalu berpikir ia benar-benar menyayangiku. Aku bahkan abai, apakah ia menyayangiku sebagai adik atau sebagai seorang gadis. Aku lengah dan menikmati kebersamaan kami seperti menikmati sepotong pie kesukaanku. Sekarang, sekarang apa yang harus aku lakukan?
“Aduh, lama-lama di depan laptop bikin mata sakit! Aku balik ke atas dulu ya, Mam!” kilahku saat merasa tiba-tiba mataku memanas.
“Ya ampun, Ran. Dijaga tuh, mata. Pakai kacamata antiradiasi, dong. Kamu ini gimana…” Mami menghentikan aktivitasnya dan mulai berjalan mendekatiku.
Dengan sigap aku membereskan buku-buku dan langsung menutup notebook. Pura-pura tak memerhatikan Mami yang menggurat cemas di wajahnya. “Ah, nggak apa-apa, Mi… bentar lagi juga hilang perihnya.”
Di kamar kubenamkan seluruh wajahku. Kelebat kenangan masa kecil menari liar tak punya kendali.
Waktu pertamakali dibangun paviliun kecil di depan rumah yang kini menjadi toko Mami, aku sedang liburan kenaikan kelas. Kami, minus kak Farhan dan kak Fadhil bermain di sana. Pipit, Rosa, Nene, Yogi juga ikut. Aku jatuh terjerembab saat berlari ingin minum ke rumah. Yogi kurus itu menggendongku ke dalam. Sementara Mami merepet panjang karena sejak awal kami dilarang bermain di sana, “Masih banyak paku, bahaya! Bla bla bla,” repet Mami sambil mencarikan Trombophob, karena kepalaku juga terbentur kayu.
Sementara itu Yogi menyeka luka dan mengoleskan Betadine di kakiku. Yogi selalu membelaku. Melindungiku, memerhatikanku walau ia tak pernah banyak bicara. Menghiburku ketika sedih, bahkan saat kakak kembarku mengusiliku, Yogi berusaha mengalihkan kesalku.
Memboncengiku di belakang sepeda BMX baru yang dibelikan Papi untuknya. Saat aku kelas dua SMA, seorang cowok mendekatiku, Yogi kelihatan protektif sekali.
“Kenapa harus dengan dia, sih?” Tanya Yogi waktu itu.
“Apaan? Siapa yang pacaran, lagi?”
“Terus, apa dong, namanya kalau bukan pacaran, pedekate?”
“Tau, ah! Dia aja tuh yang sibuk amat, sok nawarin antar ke rumah. Pinjem-pinem catatan. Lagian siapa suruh kamu ngurusin ini juga? Mami, ya?”
“Nggak!”
“Terus kenapa nanya-nanya?”
“Ng.. nggak, aku cuma…”
“Cemburu yaaa…” godaku waktu itu.
“Eh, asal! Kamu tuh, ya! Kamu tau, kan Danang punya reputasi jelek di sekolah?” kilahnya lagi.
“Oh, jadi kamu sok jadi pahlawan gitu? Ngelindungin aku… Jeh, ngikutin gosip juga rupanya.”
“Terserah kamu, deh. Kalau ada apa-apa jangan nangis nanti!” ujarnya kesal sambil berlalu.
Aku hanya tersenyum senang, rasanya bahagia sekali menyaksikan Yogi yang sedang cemburu. Ah, benarkah ia cemburu? Aku tahu sekarang, aku hanya mengiranya cemburu. Kenyataannya tidak, kan?
Dia benar-benar bersamaku. Menceriakan hari-hariku, berbagi banyak hal sejak pertama kali ia menjadi bagian keluargaku. Kakak kembarku punya dunia dan teman-temannya sendiri. Waktu bermainku justru sering dihabiskan bersama Yogi. Apalagi bulan Ramadan, kelas ekskul yang kami ambil juga sebagian besar sama.
Bagi Mami, memiliki Yogi seperti mempunyai seorang anak lelaki sekaligus anak perempuan seorang lagi. Ia punya kemampuan seorang lelaki, tetapi banyak menghabiskan waktu di rumah membantu kami. Tak pernah lagi aku memimpikan saudara perempuan di rumah ini. Sejak ada Yogi, aku tak pernah merasa sepi. Yogi seolah membuntutiku kemana saja, melindungiku kapan saja. Hingga saat kuliah, kami mulai punya jarak karena kesibukan masing-masing.
Aku tak tahu kenapa aku begitu percaya diri. Tak pernah terpikir rasa ini tak akan pernah berbalas. Ternyata bagi Yogi, aku hanya seorang adik perempuan yang menyenangkan. Selama ini tatapan sendu, tawa hangat dan perhatiannya yang kuartikan “lain” ternyata tiada. Dia tak punya perasaan “lain” untukku. Bodohnya! Aku benar-benar bodoh! Kenapa aku bisa berpikir seperti itu. Berharap menjadi istrinya? Oh, Tuhan, aku benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Bodoh! Dasar Rani bodoh!
Aku kecewa, malu, marah pada diri sendiri. Apa aku juga boleh marah pada Yogi, Mami, Papi, dan Kakak-kakakku? Kalau boleh, rasanya aku ingin marah! Tapi kenapa aku harus marah? Marah pada mereka karena tak bisa mengambilkan secuil hati milik Yogi agar ia mencintaiku lebih dari seorang adik? Aku pasti sudah gila kalau melakukan semua itu!
Sejak tahu Yogi sibuk berkenalan dengan calon istrinya, aku menenggelamkan diri dengan skripsi dan bertumpuk-tumpuk tugas dari dosen yang kubantu. Skripsiku semakin mulus, aku lebih sering menginap di kostan teman. Melihat isi rumah membuatku mual dan seolah tak sanggup melanjutkan hidup. Ah, seperti tak punya iman saja. Tuhan memang lebih tahu apa yang paling kita butuhkan, bukan apa yang paling kita inginkan, iya, kan? Tapi kali ini aku seolah kalap mengeja takdirku.
Kudengar Mami sedang sibuk mempersiapkan acara lamaran. Yogi seperti biasanya tak ingin menyusahkan Mami dan Papi, tapi kudengar lagi, Yogi seperti kebelet ingin kawin. Hah! Apa-apaan sih, dia? Sejak kapan dia bisa mengungkapkan keinginannya demikian tegas? Apakah dia benar-benar jatuh cinta dan tergila-gila pada wanita itu?
Kepalaku berdenyar, aku tak sanggup berpikir. Lebih baik kuselesaikan rancangan proposal proyek penelitian dosenku. Dua hari ini harus kuserahkan untuk didiskusikan dan ditindak lanjuti. Aku berharap proposal ini lolos, jadi aku punya banyak beban yang menguras banyak energi. Persetan dengan pernikahan Yogi! Tapi aku benar-benar tak kuat, ya, Allah.
Tapi sudahlah, dia masa lalu, seterusnya begitu. Masa lalu yang akan selalu di dekatku dengan posisi baru. Akan kubawa lari rasa remuk ini ke jurang tak bertuan!
Diary Yogi
Aku tak kuat lagi. Aku tak bisa begini terus. Rasanya aku adalah lelaki yang paling menderita di dunia ini. Selama ini aku selalu bisa menerima apapun yang Tuhan berikan untukku, tapi ini? Ya, Tuhan, betapa salahnya rasa ini. Aku harus tempuh jalan yang benar, menikah! Aku ingin menikah dalam waktu dekat ini, itu harus!
Bagamana kalau Mami dan Papi tahu? Aku benar-benar anak pungut yang tak tahu diri! Kalau sampai ada yang tahu aku telah jatuh terlalu dalam menyayanginya, lebih dari sekadar menyayangi seorang adik. Mata kacang almonnya, senyum pelanginya, derai tawanya. Belakangan, ia bukan saja mulai menutup rapat auratnya, tapi juga sikapnya. Dia di dekatku sepanjang waktu. Adakah penderitaan yang melebihi ini?
Aku bisa menafkahi hidupku, rezeki dari Allah tak pernah kuragukan. Bismillah, Ihsan akan mencarikan pendamping yang bisa melabuhkan rasa ini pada tempatnya. Rasanya aku tak mampu bernafas lagi di dekatnya. Ingin kupanggil namanya sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Tuhan, ampuni aku.
Suara sejernih lonceng milik Rani terus saja mengusikku "Haloo, Kakak Seperguruan. Anterin ke rumah Kariin, dong. Sebagai upahnya aku bakalan doakan kamu nanti dapat istri soleha, deh!"
Rani, kalau saja kamu tahu semua kenangan itu seperti godam menghantam ulu hatiku. Kenapa kamu hanya melihat sesosok kakak laki-laki dalam diriku. Aku akan buang rasa ini ke jurang tak bertuan. Kamu... tak mungkin membalasnya.
Terima kasih sudah mampir dan membaca hingga tuntas. Suka dengan fiksi-fiksi yang kutulis? Jangan lupa follow, upvote, dan resteem, ya!

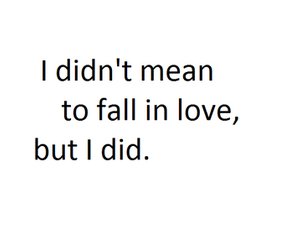
a very interesting short story, is this about your life? be patient
Nope! this is just fiction, Mate. Thanks for reading.
Are you just joined on Steemit? Welcome and enjoy the platform! Keep steem on!
Keren mom...
Makasih @chandrayunita :*
Wadus, suka kali gayanya menuangkan isi cerita, yup! "Akan kubawa lari rasa remuk ini ke jurang tak bertuan!", cakeeebbbb
Jangan sampai setragis ini remuknya ya, Kak @rahmayn. Terima kasih sudah melipir mampir.
Sedih endingnya :(
Bangeeet. Hiks! Padahal tinggal bilang doang, kan, ya? I love you or will you marry me? Salah satuu pihak aja dah!
😅😅😅
Makanya mending diungkapkam dafipada dipendam. Eh malah jadi kehilangan :(
Cerita yang menarik, meski panjang jalan ceritanya tetapi ga bosan, rika baca sampai habis 😄
Terima kasiiih. Love you full @rikanurrizki. Semoga suka, ya. Sedang belajar nulis fiksi..
Tok tok tok.. Ngejek buk??? Hahaha
Yihhaaaaaaaaa. Finally, dia datang!
Ada terasa, Fa? Kakak colek-colek pakai telepati?
Intinya...jangan melulu bermonolog. Bukalah dialog. Barangkali he feels the same. Ngapain buang ke jurang tak bertuan!
Kalau g terasa, gak fara datangin postingan kakak.. Hahaha
G bsa dibilang kak. Sejak 2009 kami g ketemu lg & sejak 2010 fara kehilangan kontaknya by accident krn hardisk fara dicuri & simcard fara ilang. Tp sblmnya fara mmg mau mengakhiri
Selebihnya cuma nyesal. Hahaha
Dunia sekarang cuma seujung jari. Masa gak bisa lagi dicari 😍
I've done many things, failed!
Fara g kenal kawannya. Dia gak kenal kawan fara. What a complicated relationship huh!
Hahaha
Search by facebook account or IG? Belum pernah terpikir hari gini ada yang memilih tidak bersosmed-ria. Hihi
((((dibahass))))
😄 😄 😄
Jawabannya nanti fara posting ya
sangat menarik... ditunggu karya karya selanjutnya
Terima kasih sudah mampir ya, Kak @sitimaghfirah 😊
Aku jadi cengeng akhir2 inj, dan membaca cerita ini jadi bikin nangis. Aku merasa jadi Rani... Hiksss
Dan akuu Yogiii. Hikss...
Yogi....kamu kok pengecut sekali sih?
Dan kamu manja kayak anak kucing!
Remuuuk yg baca...kebawa alur cerita...keren 😍
Itu balasan bagi dirimu yang rajin bikin orang ngences. Wkwkwkwkwk...